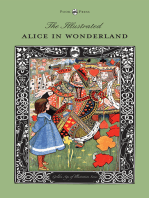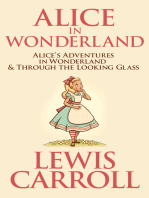Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Konflik Integrasi Sosial
Загружено:
Ratu Annisa Syifa Qatrunada0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
2 просмотров7 страницОригинальное название
KONFLIK INTEGRASI SOSIAL.docx
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
2 просмотров7 страницKonflik Integrasi Sosial
Загружено:
Ratu Annisa Syifa QatrunadaАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 7
KONFLIK INTEGRASI SOSIAL:
GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)
Mediasi Konflik Aceh & Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) – Dalam beberapa dekade terkahir, rakyat Aceh harus
mengalami kehidupan dalam suasana konflik yang disebabkan
oleh gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya ketidaksamaan
kepentingan atau pun kurangnya perhatian dari pemerintah.
Suasana konflik yang ditimbulkan oleh gerakan separatis
tersebut kemudian menarik perhatian dunia Internasional dan
adanya desakan agar konflik tersebut dapat terselesaikan.
Bagaimana mediator memposisikan dirinya dalam mediasi
penyelesaian konflik Aceh sehingga dapat teratasi
dengan baik?
Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatera bagian utara NKRI
yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekkah, ternyata
pernah terjadi suatu konflik yang tidak bisa dilupakan oleh
rakyat Indonesia khususnya masyarakat Aceh.
Dalam tulisan ini, sebelum memasuki bagaimana tahap
mediasi yang terjadi dalam upaya menyelesaikan konflik, saya
akan menyebutkan dua sejarah konflik apa saja yang pernah
terjadi di Aceh beserta tahun terjadinya.
1. Periode Daud Beureuh
Daud Beureuh dan pasukannya Dalu Islam/Tentara Isla turut
membantu Indonesia untuk lepas dari jajahan Belanda, dengan
jaminan pemerintah mau memberikan otonomi politik dalam
penyelenggaraan syariat Islam. Namun pemerintah tidak
menepati janji yang sudah disepakati. Akhirnya Daud Beureuh
memimpin pasukannya untuk melawan tentara Indonesia
sebagai bentuk proses. Pemberontakan atau pun konflik
tersebut dimulai dari tahun 1953 dan usai tahun 1959.
Pemberontakan tersebut usai tanggal 26 Mei 1959 saat Aceh
diberi status Daerah Istimewa dengan otonomi luas, utamanya
dalam bidang adat, agama, dan
pendidikan.
2. Periode Hasan Tiro dan deklarasi Gerakan Aceh
Merdeka
Konflik ini terjadi melalui pemerontakan yang diwujudkan
sebagai bentuk kekecewaan terhadap pembangunan yang
terjadi di Aceh yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Kelompok kecil
yang dipimpin oleh Hasan Tiro ini memproklamirkan
kemerdekaan di Aceh pada tanggal 4 Desember 1976 dan
memproklamirkan diri sebagai kelompok Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). Aspirasi kelompok separatis GAM sebagian
besar juga didasari latar belakang sejarah yang menyatakan
bahwa Aceh tidak pernah ikut serta dalam peraturan zaman
kolonial Belanda dan tidak pernah menjadi bagian bangsa
Indonesia yang terbentuk pada 1945. Munculnya kelompok ini
ditanggapi oleh Orde Baru dengan cara represif. Hasil dari
konflik antara ribuan anggota GAM dan tentara Republik
Indonesia yang berlarut-larut, membuat Orba mengirimkan
ribuan tentara sebagai alat untuk menumpas pemberontakan
separatis GAM. Penyerangan-penyerangan oleh GAM Mediasi
yang dianggap oleh elit politik di Aceh dan Jakarta sebagai
gangguan atas proses pembangunan yang sedang berjalan.[3]
Kekerasan Pada Masa GAM
Selama masa konflik yang sudah banyak terjadi, terjadi pula
banyak kekerasan dari konflik yang ada pada masa GAM atau
pun yang diakibatkan oleh GAM dan juga tentara Indonesia.
Setelah upaya CoHa yang gagal mewujudkan perdamaian di
Aceh tahun 2003, baku tembak senjata api terjadi di hampir
seluruh bagian Aceh. Baku tembak yang sering terjadi
dilakukan oleh pemberontak bersenjata entah itu pasukan GAM
atau pun masyarakat yang menolak GAM dan juga dari Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Selain baku tembak yang terjadi, ada
juga kasus penculikan yang dilakukan oleh ketiga pihak
tersebut. Penculikan oleh GAM dilakukan untuk meminta uang
tebusan, dan hasil tebusan yang didapat akan dipakai untuk
membiayai kegiatan mereka. Biasanya yang menjadi target
adalah pegawai pemerintah, termasuk guru-guru, juga menjadi
target. Alasannya adalah karena biasanya orang-orang
tersebut lebih kaya dan bisa memenuhi uang tebusan.
Masyarakat desa umumnya tidak menjadi target. Biasanya,
pemimpin masyarakat bertindak dalam negosiasi kedua belah
pihak dalam penculikan. Pemimpin masyarakat tersebut bisa
Kepala Desa, dan juga Kepala Mukim (read: mukim adalah
bentuk terkecil dari desa, satu desa terdiri dari beberapa
mukim). Proses negosiasi dalam penculikan ini biasanya tidak
mudah. Kekerasan yang berlaurt-larut dalam beberapa waktu
di Aceh kemudian mulai menyurut setelah terjadinya tsunami di
Aceh akhir tahun 2004. Tsunami yang menyebabkan kematian
ratusan ribu orang di sekitar Aceh dan Pulau Nias di antaranya
menyebabkan banyak tentara GAM yang tewas. Setelah
tsunami tersebut, kasus penculikan dan kekerasan sudah mulai
jarang terjadi bahkan hampir tidak pernah. Tetapi demi
terwujudnya tujuan GAM untuk Aceh yang merdeka dan
berdaulat, bantuan-bantuan internasional untuk korban tsunami
Aceh kemudian dirampok untuk keperluan tentara GAM itu
sendiri. Konflik yang berlarut-larut atas adanya perbedaan
kepentingan antara Indonesia-GAM kemudian menarik
perhatian dunia internasional untuk menanganinya. Desakan
agar Indonesia bisa menyelesaikannya dengan segera
kemudian menghadirkan pihak ketiga dari badan Organisasi
Non-Pemerintah (NGO) yang ingin segera menangani krisis di
Indonesia. Upaya perdamaian Indonesia-GAM sudah beberapa
kali dilaksanakan. Adapun pihak ketiga sebagai mediator yang
pernah hadir dalam upaya penyelesaian konflik tersebut
mengalami kegagalan. Contohnya merupakan Henry Dunant
Center (HDC). Kedua NGO itu gagal menciptakan perdamaian
antara Indonesia-GAM sebagai pihak yang berkonflik.
Kegagalan mediasi tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan
yang dilakukan oleh HDC sendiri sebagai pihak mediator, tetapi
pihak yang berkonflik yang tidak memakai akal yang rasional
dalam penyelesaiannya bahkan lebih menginginkan konflik
yang ada terus berlanjut karena dirasa lebih efektif dalam
mencapat tujuan. Perbedaan tujuan Indonesia-GAM memang
sangat bertolak-belakang sehingga membuat penyelesaian
susah terjadi. GAM menginginkan agar Aceh dapat
memisahkan diri dari Indonesia dan berdaulat penuh
sedangkan Indonesia tentu saja berjuang mempertahankan
Aceh sebagai perjuangan untuk mempertahankan keutuhan
NKRI.
Mediasi Oleh Crisis Management Iniatives (CMI)
Setelah kegagalan dari HDC, pihak mediasi lain yang mencoba
untuk meredakan konflik antara Indonesia dan GAM
adalah Crisis Management Initiatives (CMI). CMI mulai
memprakarsai perundingan damai di Aceh pada Januari 2005.
Berbagai pertemuan dan dialog informal telah berhasil
membahas dan mempertemukan isu yang paling sensitif
diantara Indonesia-GAM. GAM bersedia menarik tuntutan
merdeka dan menerima otonomi khusus. Seiring dengan hal
tersebut, kondisi di Aceh sendiri tingkat keamanannya mulai
membaik dan pemerintah merubah status darurat sipil menjadi
tertib sipil. Puncaknya, pada tanggal 15 Agustus 2005,
disepakati nota kesepahaman perdamaian antara RI dan GAM
di Helsinki. Dengan terpilihnya mantan tentara yang
mempunyai pandangan yang terbuka, Susilo Bambang
Yudhoyono sebagai presiden pada pemilu tahun 2004, prospek
untuk resolusi damai untuk konflik Aceh membaik. Dalam
waktu singkat setelah menjabat, Kalla diminta untuk mendekati
para pemimpin GAM mengenai pedamaian untuk mengakhiri
konflik. Kenyataan dalam konteks bahwa tsunami tahun 2004
menewaskan lebih dari 150,000 orang, dan ribuan lainnya
mengungsi. Kehancuran ini mendapat sorotan internasional
dan mendorong upaya bantuan kemanusiaan besar-besaran.
Tsunami juga merupakan pukulan yang cukup untuk kombatan
di kedua belah pihak baik GAM maupun tentara Indonesia.
Pada akhirnya hal itu menjadi katalis yang membawa kedua
belah pihak ke meja perdamaian untuk melakukan perjanjian
perdamaian dan memfasilitasi proses pemulihan Aceh. Dalam
proses negosiasi perdamaian konflik Aceh, wakil pemerintah
Republik Indonesia dan wakil dari Gerakan Aceh Merdeka
bertemu untuk melakukan perundingan. CMI pun dipilih
sebagai mediator karena pemimpinnya merupakan mantan
presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.
Tempat perundingan dilaksanakan, kota Helsinki, Finlandia, di
Kőnigstedt Manor antara Januari dan Agustus 2005, negosiasi
ini membawa hasil ditandatanganinya Memorandum of
Understanding (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
dan pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian ini terdiri dari
enam pokok bahasan berkenaan dengan Penyelenggaraan
Pemerintah di Aceh, Undang-undang tentang penyelenggaraan
Pemerintahan di Aceh, Partisipasi Politik, Ekonomi, Peraturan
Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Amnesti dan
reintegrasi ke dalam masyarakat, Pengaturan Keamanan,
Pembentukan Misi Monitoring Aceh, dan Penyelesaian
perselisihan. MCI sebagai mediator mampu memposisikan
dirinya dengan baik karena dia dari pihak netral yang berasal
dari NGO, dan tidak punya kepentingan politik apapun
sehingga dia mampu bersikap netral. Setelah putaran pertama,
ketika Ahtisaari merasakan bahwa hasil positif dicapai ia
mendekati Uni Eropa, yang menyetujui untuk mendanai sisa
pembicaraan. Uni Eropa juga memegang peranan kunci dalam
melaksanakan MoU dengan membentuk Aceh Monitoring
Mission (AMM) bekerjasama dengan Asosiasi Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN). Dimasukkannya perwakilan ASEAN dalam
AMM dianggap untuk menenangkan anggota pemerintahan
Indonesia yang bersikeras AMM memiliki lebih banyak
komponen lokal. Pengalaman Indonesia dengan PBB di Timor
Leste membuat hampir tidak mungkin untuk memiliki
keterlibatan langsung PBB dalam pembicaraan atau proses
implementasi.[7] Namun, satu negotiatior Indonesia
mengingatkan bahwa pemerintah juga takut bahwa kegagalan
untuk mencapai kesepakatan akan menggerogoti bantuan
internasional lanjutan sangat penting untuk upaya bantuan
tsunami.
Tercapainya perundingan antara RI-GAM dari putaran pertama
hingga putaran kelima, dan diparafnya draft MoU Helsinki pada
perundingan putaran kelima, adalah sebuah pencapaian yang
amat penting dan mendasar bagi penyelesaian konflik Aceh.
Meskipun demikian, bukan berarti dinamika perundingan
berjalan mulus. Perundingan pada putaran pertama dan kedua
sangat kritis, khususnya pada putaran kedua, karena terjadi
dead lock, tidak ada titik temu, karena posisi kedua belah pihak
yang berbeda, peran CMI dalam mencari alternatif rumusan
perundingan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam
perundingan antara RIGAM. Bagaimanapun, kepiawaian Martti
dan para pendukungnya di CMI. Martti bersedia menjadi
perantara perundingan dengan syarat bahwa Pemerintah RI
benar-benar ingin menyelesaikan persoalan separatisme GAM
secara tuntas. Alasan lain, karena Martti sebagai juru runding
adalah reputasi tokoh ini dalam persoalan kemanusiaan,
sehingga dapat menjadi jembatan untuk menciptakan
kepercayaan antara kedua belah pihak. Dari desain
perundingan, di Helsinki dapat mendorong penyelesaian konflik
secara permanen, bukan cease fire atau gencatan senjata.
Вам также может понравиться
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksОт EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyОт EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeОт EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (20018)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeОт EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookОт EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2515)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionОт EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (726)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)От EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Рейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (7770)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItОт EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (3275)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersОт EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2314)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)От EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Рейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (4345)



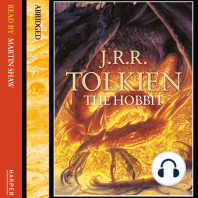




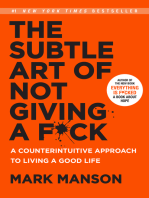

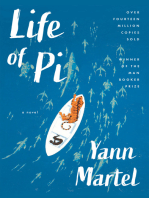
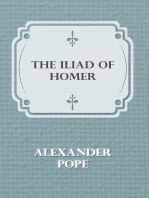








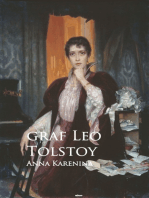
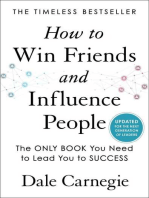


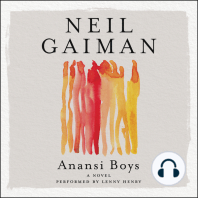
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)